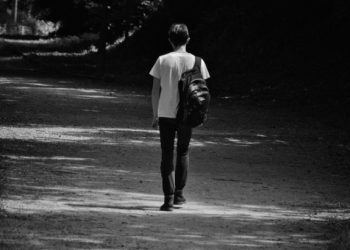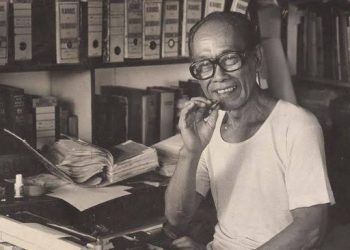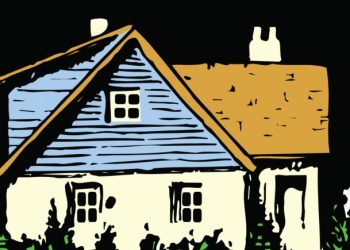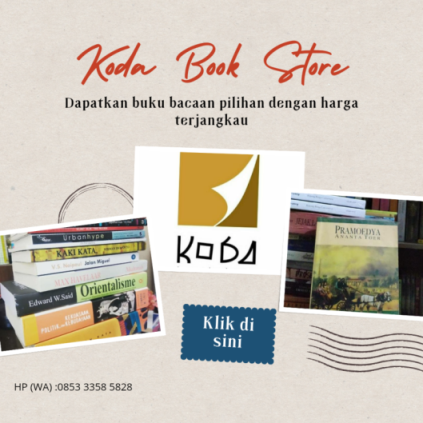Warna lokal
Terlepas dari beberapa hal yang telah dibahas di atas, cerita pendek ini mau menghadirkan sebuah kisah warna lokal untuk kita renungkan. Dalam dunia dewasa ini, nilai-nilai adat istiadat kadang terpinggirkan dengan kehadiran teknologi dan berbagai perkembangan lainnya. Cerita ini mau mengingatkan kita untuk selalu menjaga dan merawat nilai-nilai luhur warisan leluhur, berupaya sebisa mungkin agar titipan itu tidak hilang dan sirna.
Warna lokal seperti apa yang ingin ditampilkan dalam cerpen ini? Berbeda dengan pendekatan objektif yang meluluh melihat sisi intrinsik karya, atau sisi estetiknya, sebuah cerita juga akan selalu menampilkan nilai-nilai, pandangan hidup pada suatu masyarakat ataupun perorangan.
Cerita ini mau menggugat sistem pendidikan, ataupun gaya hidup masyarakat modern yang sepertinya tidak lagi mengenal adat istiadat. Hal-hal yang mistis, tidak masuk logika, telah dinilai ketinggalan zaman. Padahal, adat istiadat ataupun hal-hal mistis adalah kualitas hidup yang, bisa dikatakan, tidak bisa dipahami oleh logika.
Pengarang menampilkan tokoh Nara sebagai contoh bagaimana seorang yang berpendidikan formal bisa saja terjebak dalam logika berpikirnya sendiri, sehingga tidak lagi memahami kualitas hidup yang selama ini telah diwariskan oleh nenek moyang. Nara digambarkan sebagai tokoh yang hampir tidak bisa berbicara di depan kedua orangtuanya, seperti seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, sewaktu kedua orangtua itu berbicara tentang budaya dan adat istiadat setempat.
Pengarang menampilkan karakter Nara ini sebagai sebuah kritikan, juga sebuah peringatan, bahwa pendidikan formal bisa saja menjauhkan seseorang dari lingkungan sekitarnya, terutama dari adat istiadatnya.
Kedua orangtua Nara akhirnya menuturkan kembali, seperti mengingatkan, bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam.
Ketenaran, pendidikan, kegemerlapan hidup, yang didapat manusia, tak akan berarti apa-apa di hadapan alam semesta. Karena itu, apapun yang dilakuan manusia, harus menyelaraskannya juga dengan alam semesta. Bahkan hanya untuk aktivitas ‘makan’, manusia seharusnya selalu mengingat dengan alam, yaitu memberi hak kepada tanah sebagai lambang pemberi kehidupan.
Adegan ayah Nara menuangkan arak ke tanah sebelum diminum, adalah sebuah bentuk penghormatan terhadap sesuatu yang lebih tinggi, yang bisa memberi kehidupan di atasnya. Tanah adalah penyedia hidup, dan di atasnya seluruh makhluk hidup bisa melangsungkan kehidupannya. Semua kehidupan bisa terjadi karena ada ‘tanah’. Karena itu, rasa syukur haruslah diberikan kepadanya.
Tentu saja tanah hanyalah sebuah simbol dari sesuatu yang lebih tinggi, yang secara populer disebut dengan Tuhan. Dalam tradisi masyarakat Lamaholot, mereka menyebutnya sebagai ‘Rera Wulan Tana Ekan’.
Rera Wulan Tana Ekan adalah sebutan untuk Wujud Tertinggi, dan disimbolkan oleh matahari, bulan, tanah, dan semesta (lingkungan). Secara harafiah, rera berarti matahari, wulan ‘bulan’, tana ‘tanah’ dan ekan ‘lingkungan/ alam semesta’. Memberi minum kepada tanah, adalah tindakan syukur yang harus dilakukan oleh seorang manusia kepada alam semesta, Tuhan, Wujud Tertinggi, karena kehidupan berasal dari sana. Tentu saja rasa syukur ini tidak hanya ditujukan kepada tanah, tetapi juga kepada semua makhluk hidup yang hidup di semesta ini.
Dengan pandangan seperti itu, pengarang mau menyadarkan kita bahwa, manusia adalah satu elemen kecil dari sebuah kehidupan yang lebih besar. Manusia tidak boleh menganggap diri sebagai sebuah makhluk yang lebih besar, dan berhak menguasai yang lain. Tidak. Manusia hanyalah bagian kecil dari sebuah semesta yang lebih besar, sehingga apapun yang dia dapat dalam hidup (kebahagiaan, harta benda, dll) haruslah dibagikan juga kepada elemen pembentuk kehidupan yang lain.
Pengarang juga mau mengajak kita untuk memahami lebih mendalam bagaimana peran adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyakarat Lamaholot, fungsi adat istiadat adalah menyelaraskan hubungan manusia dengan sang Pencipta, manusia dengan alam, dan menusia dengan sesama.
Karena itu, jika seorang manusia melakukan sebuah kesalahan, seperti membakar hutan, ataupun merusakan tempat-tempat keramat, dia harus membuat ritual adat, agar bisa berdamai dengan lingkungan atau alam semesta. Jika dia tidak membuat ritual tersebut, maka alam akan menuntut balas atasnya, dan manusia itu akan mendapat kesialan dalam hidupnya. Jika tidak melakukan ritual perdamaian itu, apapun yang dia lakukan, alam akan selalu mengingatkan dirinya bahwa ada sebuah kesalahan yang belum dipulihkan.
Adegan terakhir dalam cerita, yaitu luapan emosi antara keluarga Nara dengan utusan Tuan James juga mau menggambarkan bahwa ada hal-hal krusial yang mesti dipertahankan mati-matian oleh masyarakat Lamaholot. Tanah adalah sumber kehidupan, tapi bisa juga menjadi sumber pertikaian. Sesungguhnya tidak betul jika kita mengklaim bahwa tanah adalah sumber pertikaian. Semua pertikaian tentu saja berawal mula dari manusia. Tapi konteks cerita ini mau mengingatkan bahwa tanah adalah sebuah hak yang mesti dijaga dengan baik.
Kasus pertikaian, pembunuhan, dan peperangan, kerap terjadi di Lamaholot, karena memperebutkan tanah. Semua ini terjadi karena orang-orang menganggap tanah adalah benda sakral, yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Jika bukan tanah kita, lebih bagus jangan mengklaimnya sebagai milik kita. Karena pasti ada perang. Dan memang perang terjadi pada akhir cerita ini, karena memperebutkan tanah. Pada bagian ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa perang tidak harus terjadi.
Ada cara-cara damai yang mesti dilakukan, dan adat istiadat menyiapkan ruang itu. Tapi ruang itu tidak ada dalam cerita. Dengan kata lain, pengarang membawa alur berpikir kita bahwa hanya ada satu cara mempertahankan tanah : perang. Jika hanya itu yang mau disampaikan pengarang, lalu apa gunanya tokoh Nara sebagai seorang berpendidikan?
Saya kira nilai-nilai, hal-hal agung, inilah yang ingin dibagikan pengarang kepada para pembaca melalui cerpen Mengantar Benih Padi Terakhir ke Ladang. Pengarang mau mengingatkan kepada semua orang, bahwa manusia adalah satu elemen semesta, dan untuk menjaga kelangsungan semesta, manusia mesti bersyukur, berbagi, dan menghargai semua ciptaan yang ada di dunia ini.
Dari sisi inilah, cerpen ini menjadi sebuah karya yang mesti menjadi bahan permenungan seluruh umat manusia, sekaligus sesama di antara kita saling mengajak untuk menghargai bumi yang kita cintai ini.
Sebagai penutup, saya ingin menyinggung kembali bahwa ada dua hal penting yang bisa kita lihat dari sebuah karya sastra. Yang pertama adalah unsur estetiknya, yaitu hal-hal instrinsik pembentuk karya. Kedua ialah nilai-nilai hidup, pandangan hidup masyarakat, dan berbagai keagungan lain yang ingin disampaikan oleh sang pengarang.
Orang kadang menyebut kedua hal ini sebagai perpaduan antara isi dan bentuk. Dan sebagai pengarang, patut dipertimbangkan secara baik kedua unsur ini. Dari sisi bentuk atau estetik karya, cerpen Mengantar Benih Padi Terakhir ke Ladang ini masih memiliki beberapa kekurangan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Namun, cerpen ini menghadirkan warna lokal, atau warisan agung leluhur, yang perlu kita renungkan bersama. *